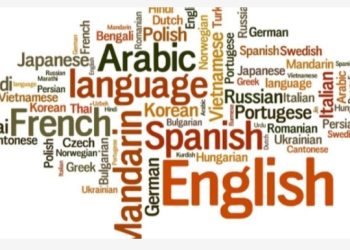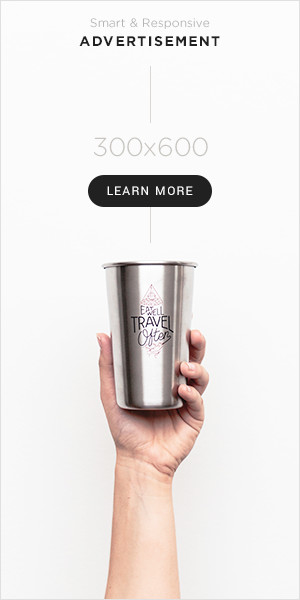CACING TEMBILUK atau dalam nama latinnya Bactronophorus thoracites, sebenarnya termasuk dalam kelompok moluska.
Moluska adalah hewan yang tidak memiliki kerangka tulang belakang dan memiliki tubuh yang lunak.
Namun, karena secara fisik mirip dengan cacing, di Indonesia hewan ini kemudian sering disebut sebagai cacing.
Ukuran dari cacing tembiluk ini jauh lebih besar daripada cacing tanah. Tubuhnya juga tidak mengeluarkan warna yang mencolok, malah cenderung lebih ke putih pucat.
Seperti rayap, cacing ini dapat memakan dan membentuk lubang pada batang kayu yang terendam udara.
Cacing yang sering ditemukan di wilayah Timur Indonesia, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua ini juga dapat menjadi salah satu penyebab kerusakan pada kayu yang digunakan untuk membuat perahu nelayan.
Kendati sebenarnya mereka bermanfaat sebagai pengurai, warga seringkali menganggap hewan ini sebagai hama.
Oleh karena itu, untuk mengurangi populasi tembiluk, warga akhirnya menjadikan cacing ini sebagai santapan.
Cacing ini telah menjadi salah satu hidangan khas suku Dayak Bulusu di Kalimantan Utara dan suku Kamoro di Papua.
Di Papua sendiri, hewan bertubuh licin ini dikenal dengan nama tambelo.
Nutrisi berupa karbohidrat, protein, dan lemak yang dikandung tembiluk ternyata dapat menjadi obat bagi beberapa penyakit, seperti rematik, batuk dan flu. (*/ted)